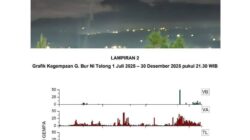TIGA puluh lima hari telah berlalu sejak amarah bumi meluap di Aceh Tamiang. Banjir ekologis yang membawa lumpur pekat bukan sekadar menyisakan genangan, tetapi meninggalkan luka panjang di tubuh kampung-kampung—terutama di wilayah perkotaan dan pinggiran kota yang selama ini dianggap paling “dekat” dengan pusat pemerintahan.
Di balik angka resmi dan laporan situasional, realitas di lapangan menunjukkan fakta pahit: pemulihan belum benar-benar menyentuh kehidupan warga. Lumpur setinggi betis hingga paha masih menggumpal di halaman rumah, menyusup ke ruang tamu, dapur, hingga kamar tidur.
Di banyak sudut Kota Kualasimpang, bau tanah basah bercampur limbah rumah tangga menguar setiap pagi, seolah menjadi penanda bahwa bencana belum usai—ia hanya berganti rupa.
Bencana ekologis Aceh Tamiang tercatat meluluhlantakkan 208 kampung dari total 216 kampung di 12 kecamatan. Hampir seluruh wilayah terdampak. Namun ironi justru terlihat di kawasan perkotaan dan pinggiran: wilayah yang secara logika seharusnya lebih cepat pulih, justru masih terkatung-katung tanpa kepastian.
“Ini bukan soal kami tidak sabar,” kata Andi, warga Kampung Sriwijaya, Kecamatan Kota Kualasimpang. “Ini soal rumah kami yang sudah tidak bisa dihuni, dan lumpur yang tidak mungkin dibersihkan dengan tenaga manusia.”
Kota yang Terdiam oleh Lumpur
Kampung Sriwijaya berada tak jauh dari pusat kota. Gang-gang sempit yang dahulu menjadi jalur aktivitas warga kini berubah menjadi lorong lumpur.
Di beberapa titik, permukaan tanah mengeras di atas, tetapi tetap lembek di bawah—menjebak kaki siapa pun yang mencoba melintas.
Banyak rumah telah ditinggalkan pemiliknya. Sebagian mengungsi ke rumah kerabat, sebagian lain bertahan di tenda darurat seadanya. Perabot rumah tangga ditumpuk di sudut, tak sedikit yang dibiarkan rusak dan membusuk. Anak-anak kehilangan ruang bermain, orang tua kehilangan tempat kembali.
Andi mengaku, rumahnya yang berada di belakang SMA Al Wasliyah, Gang Mustika, adalah salah satu yang terparah.
“Lumpurnya sangat tinggi, masih keos sampai sekarang. Kami sudah meninggalkan rumah semua. Tidak mungkin dibersihkan pakai tenaga manusia. Kami ingin pemerintah hadir di sini.”
Kondisi ini menegaskan satu fakta penting: fase tanggap darurat boleh saja berlalu, tetapi fase pemulihan belum benar-benar dimulai.
ANTARA EMPATI DAN KETERBATASAN NEGARA
MENARIKNYA, di tengah kekecewaan itu, Andi dan warga lainnya tidak sepenuhnya melayangkan tudingan kepada pemerintah daerah. Ada kesadaran kolektif bahwa bencana ini melampaui kapasitas lokal.
“Saya tidak menyalahkan pemerintah Aceh Tamiang dan provinsi,” ujar Andi. “Kuncinya ada di pusat, di Jakarta.”
Pernyataan ini bukan tanpa dasar.
Skala kerusakan yang hampir menyentuh seluruh wilayah kabupaten, ditambah kompleksitas penyebab ekologis—kerusakan hulu, sedimentasi sungai, perubahan tutupan lahan—menjadikan bencana ini bukan lagi peristiwa lokal biasa.
Namun hingga hari ke-35, status bencana nasional belum ditetapkan. Padahal, penetapan tersebut akan membuka akses lebih luas terhadap sumber daya, alat berat, pendanaan, dan koordinasi lintas kementerian.
Tanpa status nasional, pemerintah daerah bergerak dengan segala keterbatasannya: anggaran terbatas, alat berat minim, dan beban administratif yang berat. Akibatnya, pemulihan berjalan lambat, bahkan nyaris stagnan di beberapa titik.
LUMPUR SEBAGAI SIMBOL KETIMPANGAN PENANGANAN
DI LAPANGAN, lumpur bukan sekadar material sisa banjir. Ia menjadi simbol ketimpangan penanganan bencana. Di beberapa wilayah tertentu, pembersihan mulai terlihat—meski terbatas. Namun di banyak kampung lain, terutama kawasan padat penduduk, lumpur dibiarkan mengering dengan sendirinya.
Padahal, lumpur yang mengendap terlalu lama berpotensi menimbulkan masalah kesehatan serius: penyakit kulit, gangguan pernapasan, hingga pencemaran sumber air. Belum lagi dampak psikologis warga yang dipaksa hidup dalam ketidakpastian.
Andi berharap hal paling sederhana: alat berat masuk ke lorong-lorong kampung.
“Kami ingin lorong masuk ke rumah kami direcovery dulu. Supaya kami bisa bersihkan rumah. Kalau tidak, kami mau pulang ke mana?”
Harapan itu terdengar sederhana, namun hingga kini belum terwujud.
BENCANA YANG BELUM DIAKUI SEPENUHNYA
BENCANA ekologis Aceh Tamiang menyimpan pertanyaan besar: mengapa peristiwa sebesar ini belum mendapatkan atensi nasional yang memadai? Apakah karena lokasinya jauh dari pusat kekuasaan? Atau karena dampaknya dianggap tidak “cukup dramatis” secara politik?
Padahal, hampir seluruh kampung terdampak. Aktivitas ekonomi lumpuh.
Ribuan warga kehilangan tempat tinggal sementara. Ini bukan sekadar banjir musiman—ini adalah akumulasi panjang kerusakan ekologis yang kini menagih harga mahal.
Andi dan warga lain tidak menuntut kemewahan. Mereka hanya ingin negara hadir secara nyata, bukan sekadar melalui pernyataan atau kunjungan simbolik.
Andi (Warga Kampung Sriwijaya, Kota Kualasimpang): “Kami semua sudah meninggalkan rumah masing-masing karena lumpurnya sangat tinggi. Tidak mampu kami bersihkan. Tolonglah pak, kami ingin pemerintah hadir di sini.”
MENUNGGU NEGARA DI LORONG-LORONG SUNYI
DI LORONG-LORONG sempit Kampung Sriwijaya, waktu berjalan lambat. Lumpur mengering perlahan, tetapi harapan warga justru kian menipis. Tiga puluh lima hari bukan waktu yang singkat bagi mereka yang kehilangan rumah, rasa aman, dan kepastian.
Aceh Tamiang hari ini adalah cermin tentang bagaimana bencana ekologis sering kali selesai di atas kertas, tetapi belum selesai di kehidupan nyata. Selama status, kebijakan, dan keberpihakan masih tertahan di meja pusat, lumpur akan tetap tinggal—bukan hanya di lantai rumah, tetapi di ingatan kolektif warga.
Dan di balik pintu-pintu rumah yang tertutup lumpur, masyarakat masih menunggu satu hal paling mendasar: kehadiran negara yang benar-benar turun ke lorong-lorong sunyi tempat mereka pernah menyebutnya rumah.(S04)