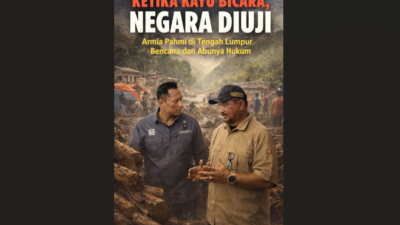DI UJUNG TIMUR ACEH TAMIANG, ombak Selat Malaka masih berdebur pelan di tepian Kuala Peunaga.
Sekilas kampung itu tampak damai: anak-anak berlari di antara jemuran jaring ikan, aroma belacan menyeruak dari dapur-dapur kayu, dan suara perahu motor kecil sesekali memecah sunyi pagi.
Tapi di balik ketenangan itu, ada luka lama yang belum sembuh; luka yang bukan berasal dari laut, melainkan dari manusia sendiri.
Tahun 1998, laut menelan kampung ini. Rumah-rumah tenggelam, surau hilang, dan 176 keluarga terpaksa pindah ke daratan.
Mereka membangun kembali hidup yang patah, sampai gelombang Tsunami 2004 menghancurkan segalanya sekali lagi.
Namun, seperti karang yang tetap berdiri dihempas badai, warga Kuala Peunaga kembali bertahan. Pemerintah membangunkan rumah baru lewat program BRR tahun 2006. Dari reruntuhan, lahirlah peradaban baru di tanah pengungsian itu.
Kini, dua dekade berlalu, kampung ini telah tumbuh menjadi 713 keluarga. Warganya menggantungkan hidup dari belacan Tuktuk, hasil olahan udang sabu yang jadi kebanggaan Aceh Tamiang.
Sebagian lainnya nelayan, sebagian lagi petani sawit. Kuala Peunaga semestinya menjadi simbol ketabahan; tapi belakangan, kisahnya berubah getir.
Jejak yang Busuk di Balik Belacan
Tahun-tahun lalu, di bawah kepemimpinan Datok Muhammad Yusuf (2012–2018), kampung ini ternyata disusupi bau amis lain; korupsi.
Lembaga Advokasi Hutan Lestari (LembAHtari) menemukan bukti penyelewengan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp212 juta lebih. Uang itu semestinya untuk pembangunan dan pemberdayaan warga, tapi justru mengalir entah ke mana.
Muhammad Yusuf dan Sekdes-nya, Kamaruddin, disebut bersekongkol.Hasil audit Inspektorat membenarkan temuan itu; Yusuf diduga mengambil Rp109 juta, Kamaruddin Rp103 juta. Dari jumlah itu, hanya Rp10 juta dan Rp300 ribu yang dikembalikan, sisanya menguap seperti buih di lautan.
Ironisnya, keduanya masih hidup bebas, tanpa proses hukum yang jelas hingga kini (2025). “Uang itu uang rakyat, uang kampung,” ucap Warianto, 60 tahun, warga yang menyaksikan perjalanan panjang Kuala Peunaga.
Ia duduk di teras rumahnya, menatap laut yang tenang, tapi matanya berkabut oleh amarah.
“Kami dulu kehilangan rumah karena air laut. Sekarang kejujuran kami yang hilang karena manusia.”
Sayed Zainal M, Direktur Eksekutif LembAHtari, menegaskan kasus ini tidak boleh didiamkan.
“Kami sudah sampaikan hasil investigasi ke Inspektorat. Tapi hingga kini, belum ada langkah hukum nyata,” katanya. “Ini bentuk pembiaran. Uang itu harus dikembalikan ke kas desa, atau hukum harus bicara.”
Menurut Sayed, bukan hanya soal uang, tapi soal pengaruh buruk yang masih dimainkan oleh Kamaruddin. Ia disebut masih menggerakkan sebagian warga, membangun oligarki kecil di kampung pesisir itu.
“Mereka masih memanfaatkan celah dan loyalitas lama. Kami akan bongkar semuanya,” janji Sayed.
Ketika Kejujuran Tenggelam
Di rumah kayu sederhana, Samsuddin A., 62 tahun, menatap selembar kwitansi lama; bukti bantuan desa yang tak pernah dia rasakan.
“Kalau uang itu benar dipakai untuk rakyat, jalan kampung ini sudah bagus, anak-anak bisa belajar dengan nyaman,” katanya lirih. “Tapi lihatlah, kampung kami masih begini.”
Suara Samsuddin berat, seperti membawa beban sejarah yang panjang. Ia tahu Kuala Peunaga pernah dikubur oleh dua bencana besar, tapi baginya yang lebih menyakitkan adalah ketika warga sendiri menjadi pelaku ketidakadilan.
Sementara M. Yusuf Musa, 53 tahun, menuntut ketegasan.“Kalau uang itu tidak dikembalikan, laporkan saja ke aparat hukum. Jangan diamkan. Diam itu sama saja membiarkan kampung ini tenggelam lagi, tapi kali ini bukan karena laut.
”Di sisi lain, Penjabat Datok Penghulu Sayed Anwar kini berusaha membenahi kepercayaan publik. Ia sadar, memulihkan infrastruktur jauh lebih mudah daripada memulihkan moral.“Kami ingin kampung ini bersih dan maju,” katanya pelan. “Kami ingin warga percaya lagi pada pemerintahan kampung.”
Antara Ombak dan Oligarki
Di Kuala Peunaga, ombak memang sudah jinak. Tapi arus kepentingan masih sering berputar di bawah permukaan.Bagi sebagian warga, korupsi mungkin tampak seperti angka-angka di kertas laporan.
Tapi bagi kampung yang pernah kehilangan segalanya, setiap rupiah adalah nyawa kecil yang menyalakan harapan hidup.
Kuala Peunaga seharusnya jadi kisah kebangkitan; tapi selama jejak korupsi itu masih menganga, ia akan terus jadi peringatan bahwa kehancuran tidak selalu datang dari laut.
“Air laut menenggelamkan rumah kami dulu, tapi jangan biarkan manusia menenggelamkan kejujuran kami sekarang.”
[Warianto, warga Kuala Peunaga]
Laut mungkin sudah reda, tapi gelombang ketidakadilan masih bergulung di daratan. Kuala Peunaga telah tiga kali membangun rumah dari puing, tapi kali ini mereka harus membangun sesuatu yang lebih sulit; kepercayaan.
Dan di kampung yang dulu pernah ditelan ombak, masyarakat kini belajar bahwa korupsi bisa jauh lebih dalam daripada laut itu sendiri.
Apakah bgnda ingin saya lanjutkan dengan ilustrasi digital art versi ini; menggambarkan suasana kampung pesisir dengan laut tenang di kejauhan, warga menatap matahari senja, dan bayangan dua sosok yang melambangkan korupsi di belakang mereka, agar maknanya lebih simbolik dan menyentuh?. [].