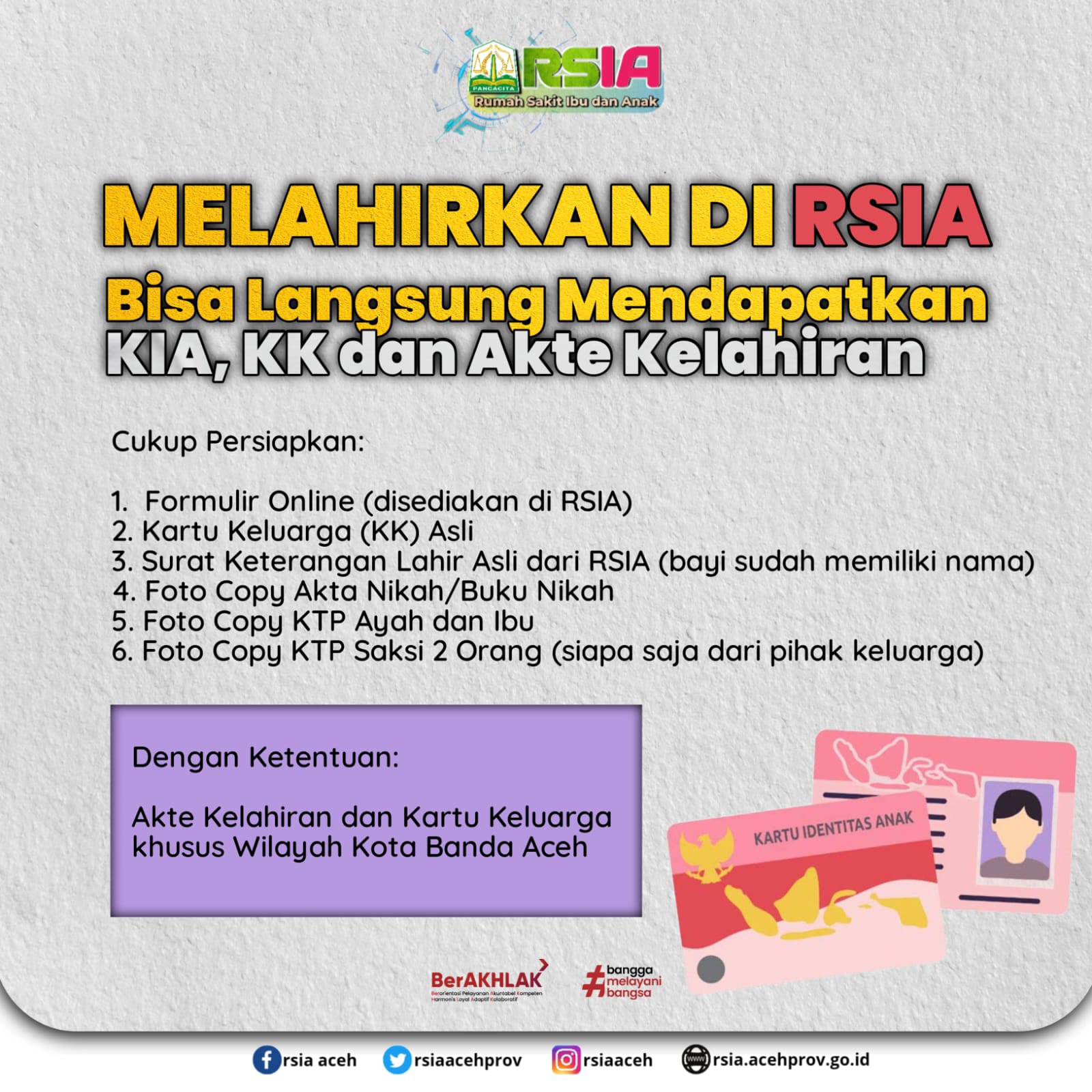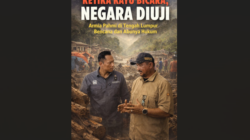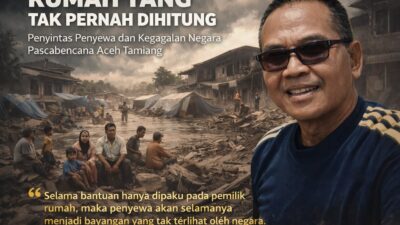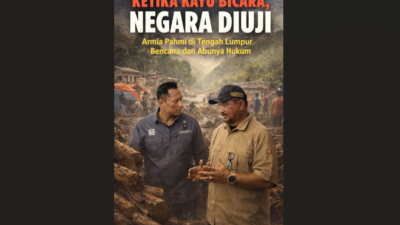Di Tanah Kaya tapi Tak Menghidupi
DI BALIK BARISAN derrick tua yang berderit tertiup angin, aroma minyak mentah masih menetes dari pipa-pipa besi peninggalan masa lalu. Di jalan tanah yang berlubang, anak-anak berlarian tanpa alas kaki, tertawa di tengah debu dan genangan hujan semalam.
Di sebuah rumah papan yang lapuk di tepi desa, Nurhayati (48) tengah menanak nasi. “Orang tua kami bilang tanah ini kaya,” ujarnya perlahan sambil menatap keluar jendela. “Tapi sampai sekarang, saya belum tahu di mana letak kayanya itu.”
Ia tersenyum getir. Tak jauh dari rumahnya berdiri pagar tinggi bertuliskan Pertamina EP Rantau. Di balik pagar itu, minyak dipompa dari perut bumi Aceh Tamiang setiap hari [mengalir ke kas negara, bukan ke dapur rakyat].
Kontras itu begitu mencolok: di atas tanah yang mengandung emas hitam, warganya hidup pas-pasan, menunggu janji kesejahteraan yang tak kunjung tiba.
Kisah yang Berulang Sejak Zaman Kolonial
Bagi Dr. Usman Lamreung, Direktur Lembaga Emirates Development Research (EDR), Aceh Tamiang adalah cermin klasik ketimpangan sosial.
“Sejak zaman Belanda, minyak di Rantau telah menjadi rebutan, tapi tidak pernah menjadi berkah bagi penduduknya,” ujarnya.
Rantau memang wilayah bersejarah. Di awal abad ke-20, Belanda menggali sumur pertama di Sumatra. Setelah kemerdekaan, giliran perusahaan milik negara yang melanjutkan eksploitasi.
Namun, warisan panjang itu tak banyak mengubah nasib rakyat. Sumur-sumur tua masih meneteskan minyak, sementara laporan produksi tiap tahun menunjukkan angka fantastis. Kekayaan itu terus mengalir [ke pusat, ke perusahaan, tapi jarang ke kantong warga].
Saat Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) disahkan pasca damai Helsinki, rakyat berharap sejarah berubah arah. Mereka percaya, kini giliran Aceh menentukan nasib sendiri. Tapi dua dekade berlalu, mimpi itu masih terhenti di atas kertas.
Ketika Diam Tak Lagi Cukup
Kemarahan yang lama terpendam akhirnya pecah. Awal Oktober lalu, ratusan warga menduduki kantor Pertamina EP Rantau. Spanduk mereka sederhana:
“Kami Bukan Penonton di Tanah Sendiri.” Abu Hamzah, salah satu tokoh masyarakat, berdiri di atas mobil bak terbuka. Suaranya parau tapi tegas.
“Kami tidak menolak investasi. Kami hanya menuntut keadilan. Kami ingin tahu ke mana uang CSR itu mengalir, dan kenapa BPMA tidak dilibatkan dalam keputusan tentang minyak kami sendiri.”
Suara itu menggema di antara pagar dan bendera perusahaan. Di wajah para warga tersimpan amarah yang tenang; bukan untuk menghancurkan, tapi untuk didengar. Bagi mereka, protes itu bukan sekadar politik, tapi jeritan nurani.
UUPA dan Kedaulatan yang Tertunda
Dua puluh tahun lalu, Aceh dijanjikan kedaulatan atas kekayaannya sendiri. Melalui UUPA, dibentuklah Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), lembaga yang diharapkan menjadi simbol otonomi energi Aceh.
Namun janji itu memudar seiring waktu. Saat kontrak Pertamina EP Rantau diperpanjang oleh SKK Migas tanpa pelibatan BPMA, rakyat merasa dikhianati.
“Bukan karena kami benci pemerintah pusat,” ujar seorang aktivis muda. “Tapi karena kami merasa hak kami dilangkahi oleh sistem yang seharusnya melindungi kami.” Seorang staf BPMA di Banda Aceh bahkan mengaku tak berdaya. “Kami tahu masyarakat kecewa,” katanya lirih. “Tapi banyak keputusan berada di luar jangkauan kami.”
Kalimat sederhana itu menggambarkan, betapa kedaulatan yang dijanjikan masih tersandera di antara meja birokrasi dan kepentingan politik.
CSR: Antara Plakat dan Kenyataan
Di sepanjang jalan menuju Rantau, papan bertuliskan “Program CSR Pertamina EP: Bersama Membangun Negeri” berjejer di tepi jalan. Tapi di balik slogan itu, warga mengeluh program yang tidak menyentuh kebutuhan nyata.
“Dulu pernah dibangun taman baca, tapi sekarang rusak dan kosong,” ujar Salmi, guru di Desa Suka Jadi. “Air bersih saja kami masih beli. Katanya tidak masuk dalam program CSR.
”Usman Lamreung menyebut hal itu sebagai “kegagalan tanggung jawab sosial yang substansial”. Menurutnya, CSR mestinya membangun kemandirian ekonomi warga, bukan berhenti pada simbol. “Tanpa transparansi dan akuntabilitas, CSR hanya jadi papan nama, bukan jembatan kesejahteraan,” tegasnya.
Rakyat yang Ditinggalkan di Tengah Kekayaan
Data BPS menunjukkan Aceh Tamiang masih memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Sebagian besar penduduk bertani atau bekerja serabutan. Ironis, karena mereka tinggal di atas ladang migas aktif.Di Desa Alur Cucur, Iskandar (27) menatap tangannya yang kasar.
“Saya sudah melamar kerja ke Pertamina, tapi tak diterima. Katanya butuh pengalaman dan ijazah tinggi. Siapa yang mau sekolah kalau dari kecil harus bantu orang tua?” katanya.
Kisah Iskandar hanyalah satu dari ribuan potret senyap, tentang generasi yang tumbuh di bawah gemuruh mesin industri, tapi tak pernah menikmati hasilnya.
Antara Pusat dan Daerah
UUPA menjanjikan bagi hasil migas 70% untuk Aceh. Tapi dalam praktiknya, mekanisme itu sering kabur. “Selama Aceh tidak punya posisi tawar kuat, kedaulatan energi hanya akan menjadi slogan,” ujar Usman Lamreung.
Ia menilai pemerintah pusat masih memperlakukan Aceh sebagai “penerima kebijakan”, bukan mitra sejajar. Padahal, menurutnya, Aceh memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk mengelola migas sendiri, asal diberi kepercayaan dan ruang politik yang nyata.
Di Tengah Luka, Masih Ada Harapan
Meski kecewa, rakyat Aceh Tamiang tidak menyerah. Di beberapa gampong, kelompok muda mulai membangun koperasi dan pelatihan wirausaha kecil. Mereka tak mau lagi hanya menunggu belas kasihan CSR.
“Kalau pemerintah lambat, kami mulai dari bawah,” kata Siti Rahma, aktivis perempuan di Kecamatan Banda Mulia. Ia percaya, kemandirian adalah bentuk perlawanan paling damai yang bisa mereka lakukan.
Janji di Langit Aceh
Malam tiba di Rantau. Lampu-lampu di kawasan produksi Pertamina menyala terang, memantulkan cahaya pada pipa-pipa baja yang dingin. Sementara di kampung seberang, lampu minyak kecil masih menerangi dapur-dapur sederhana.
Kontras itu seperti cermin dari sebuah bangsa kecil di ujung Sumatra: kaya di bawah tanah, miskin di permukaan.
Bagi Nurhayati, Abu Hamzah, dan ribuan warga lain, perjuangan belum selesai. Mereka tak meminta keajaiban—hanya keadilan.
“Kami tidak menuntut banyak,” kata seorang warga Rantau. “Kami hanya ingin hak kami dihormati, agar tanah yang kami cintai ini memberi hidup, bukan sekadar harapan.” [].